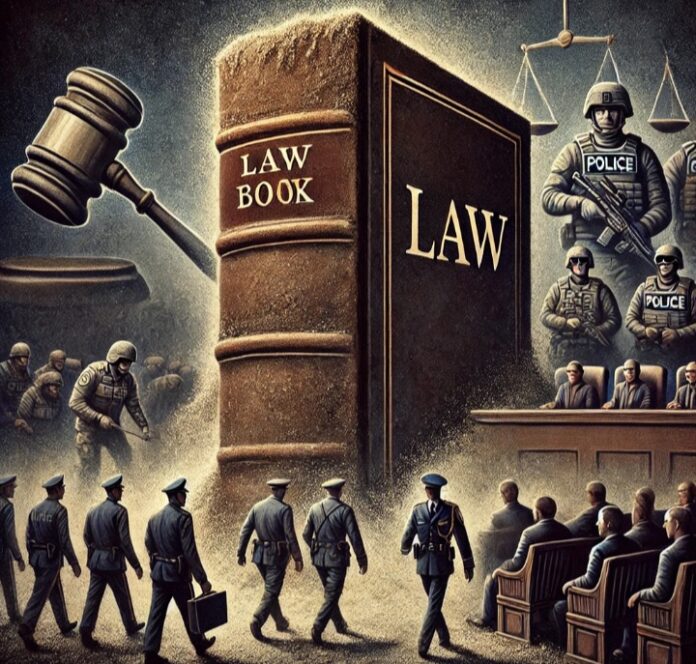Negara Hukum yang Lupa Hukum: Ironi di Balik Revisi UU TNI dan Pola Ketidakpatuhan Polri
Oleh : Paul MS d’Flo
Pemerhati kebijakan Publik
Aktifis Pers Kampus Mahasiswa 90an
Selamat datang di Republik Paradoxiana, sebuah negeri di mana hukum adalah panglima, tapi panglima pun bisa diabaikan jika tak sesuai selera penguasa. Baru-baru ini, DPR dengan penuh semangat mengesahkan revisi UU TNI, mengubah beberapa pasal krusial, termasuk Pasal 47 yang kini dengan resmi mengizinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di 14 Kementerian/Lembaga. Tidak lebih, tidak kurang. Sangat terukur, sangat rapi.
Mabes TNI pun tak ingin bertele-tele. Dengan lugas dan tegas, mereka memastikan bahwa prajurit yang menjabat di luar 14 institusi tersebut harus segera pensiun dini atau mengundurkan diri. Panglima TNI sendiri menegaskan aturan ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap UU No. 34/2004 yang telah diperbarui. Semua jelas, semua transparan. Begitulah seharusnya negara hukum bekerja.
Namun, mari kita geser sedikit layar ke sisi lain panggung: Polri.
Lembaga yang namanya begitu harum sebagai penegak hukum, namun belakangan lebih dikenal sebagai pelanggar hukum yang mereka buat sendiri. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 28 Ayat 3 dengan gamblang menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil di luar kepolisian HARUS PENSIUN DINI. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada ruang kompromi. Seharusnya.
Lalu, kita lihat kenyataannya.
Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo dengan bangga melantik Komjen (Purn?) Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu pertanyaan mendasar, di mana surat pensiun dini beliau? Oh, tunggu… mungkin terselip di bawah tumpukan laporan kasus yang tidak selesai. Atau mungkin memang tidak pernah ada.
Dan ini bukan kasus tunggal. Ada 59 perwira tinggi Polri yang tetap bertugas di kementerian tanpa mengundurkan diri, seolah-olah hukum hanyalah deretan kata di atas kertas yang tak lebih berharga dari tiket parkir.
Negara ini katanya berlandaskan hukum, tetapi bagaimana mungkin hukum bisa berdiri tegak jika lembaga penegaknya justru yang pertama kali melanggarnya? Jika TNI saja bisa patuh pada aturan main, mengapa Polri merasa memiliki hak istimewa untuk tidak tunduk pada hukum yang sama?
Dan lebih tragis lagi, di mana peran Presiden? Seorang kepala negara yang seharusnya menjadi simbol supremasi hukum, malah menjadi pihak yang mengesahkan pelanggaran hukum dengan tangan terbuka. Apakah ini bentuk “kecolongan” atau justru bentuk pembiaran yang disengaja?
Ironi ini semakin terasa getir ketika kita mengingat bagaimana selama 10 tahun terakhir, negeri ini dijadikan laboratorium kekuasaan absolut. Aturan ditulis, lalu dihapus. Hukum dibuat, lalu dilanggar. Negeri ini diacak acak, bukan oleh rakyatnya, tetapi oleh segelintir elit yang merasa berhak atas semua celah dan kelonggaran.
Maka, mari kita bertanya dengan lantang:
Jika hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah, lalu untuk siapa sebenarnya hukum ini dibuat?
Jika aparat penegak hukum justru menjadi pelanggar aturan, lalu siapa yang akan mengawasi mereka?
Jika Presiden sebagai kepala negara tidak mampu menegakkan aturan, lalu masih pantaskah kita menyebut ini negara hukum?
Negara ini bisa baik jika semua pihak terutama mereka yang berada di puncak kekuasaan bersedia tunduk pada aturan yang mereka buat sendiri.
Sudah waktunya kita berhenti bermain-main dengan hukum. Negara ini bukan milik segelintir orang yang bisa mempermainkan aturan seenaknya.
Jadi, jika ingin negeri ini kembali tertata setelah satu dekade porak poranda oleh kepentingan kuasa, mulailah dengan satu prinsip sederhana: hormati hukum, tegakkan aturan, dan jangan pernah kompromi terhadap pelanggaran terutama jika yang melanggar adalah mereka yang seharusnya menegakkannya.