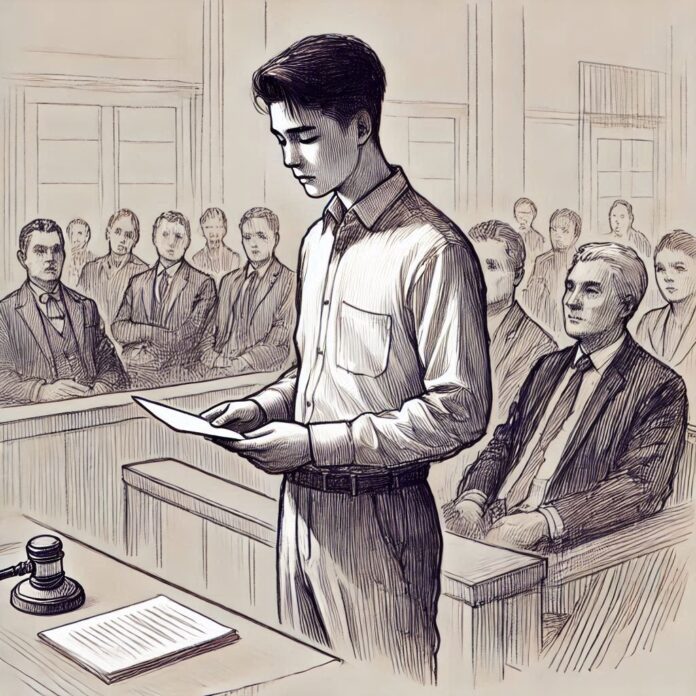Anak-anakku, Papa Bukan Koruptor
Cerpen
Wahyu Ari Wicaksono
Panglima TNI Sematkan Bintang Yudha Dharma Utama Kepada Menhan RI
Panglima TNI Sematkan Bintang Yudha Dharma Utama Kepada Menhan RI
JAKARTASATU.COM-- Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyematkan tanda kehormatan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia,...
Kalau Negara Tak Sanggup Menghadapi Aguan, Jadikan Banten 48 Jam Wilayah Bebas Hukum Untuk...
Kalau Negara Tak Sanggup Menghadapi Aguan, Jadikan Banten 48 Jam Wilayah Bebas Hukum Untuk Mengadili Aguan
Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat
Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki...
Nelayan Migran Indonesia Gugat Raksasa Seafood AS, Dugaannya Kerja Paksa
JAKARTASATU.COM- Greenpeace Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan solidaritas serta dukungan penuh terhadap sekelompok nelayan migran Indonesia yang mengajukan gugatan terhadap perusahaan...
Terungkap di Persidangan Semua Ijasah Jokowi Tidak Ada Aslinya
Terungkap di Persidangan Semua Ijasah Jokowi Tidak Ada Aslinya
Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
(Who is Jokowi, whose son is Jokowi?)
Kupasan...
Dilema Moral dalam Jurnalisme: Antara Gudeg Adem Ayem dan Jokowi
Dilema Moral dalam Jurnalisme: Antara Gudeg Adem Ayem dan Jokowi
Oleh: Sarimin A. SaimanPEKAN lalu, rombongan wartawan senior dan pernah menjadi Pimpinan Redaksi dan masih...